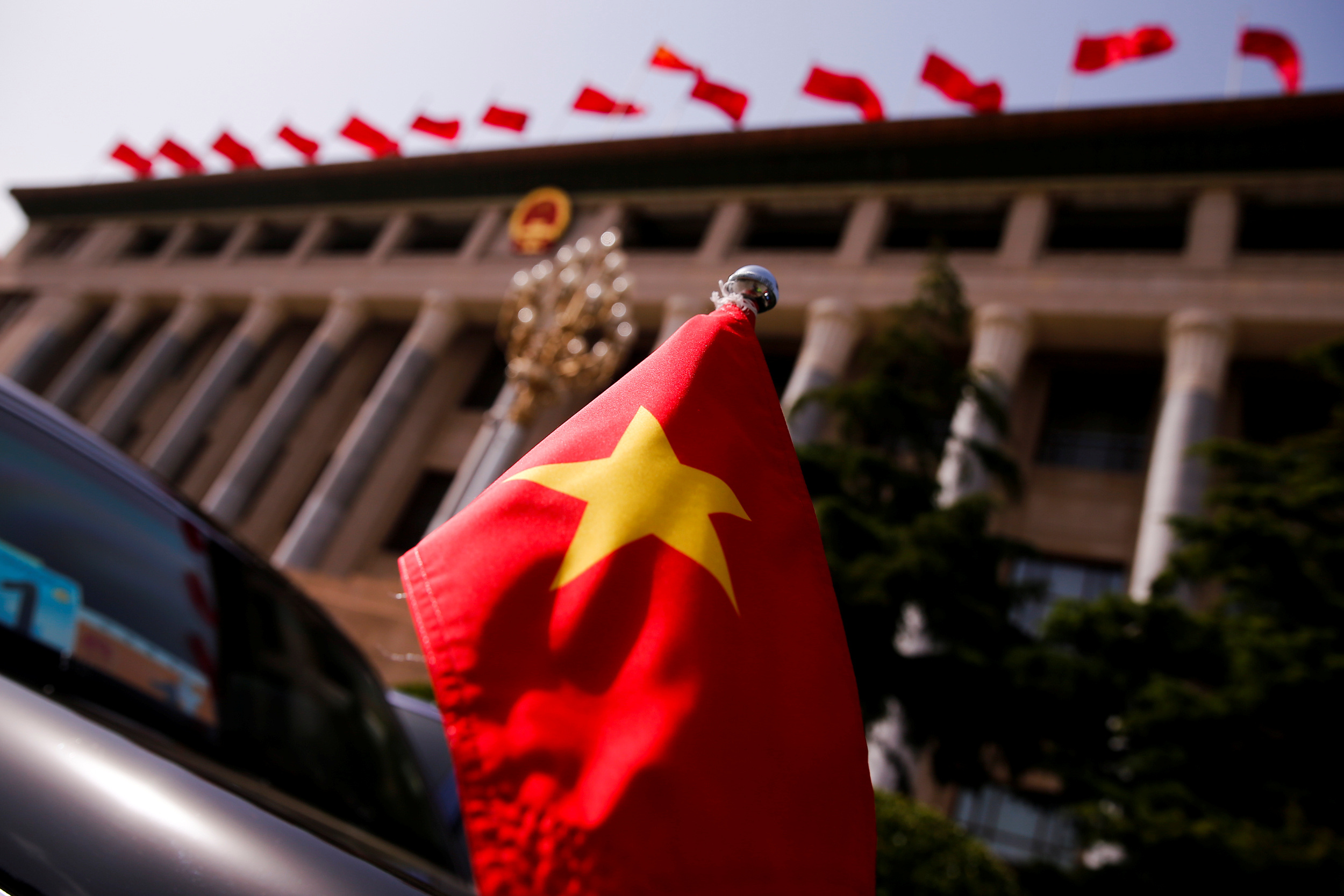JAKARTA, Cobisnis.com - Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 kembali diperingati dengan tema “Bakti Transportasi untuk Negeri”. Tema ini terdengar kuat, seakan menegaskan bahwa transportasi adalah pengabdian nyata bagi masyarakat luas.
Namun di lapangan, wajah angkutan umum justru menunjukkan kenyataan sebaliknya, di banyak kota angkutan umum semakin terpinggirkan, dan masyarakat makin bergantung pada kendaraan pribadi.
Pertanyaannya, apakah semangat bakti itu benar-benar sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari warga, atau Harhubnas hanya berhenti sebagai seremoni tahunan belaka?
Jakarta yang dianggap paling maju dengan jaringan TransJakarta, MRT, LRT, dan Jaklingko pun pada 2024 hanya mencatat tingkat penggunaan angkutan umumnya sekitar 18,86 persen. Angka ini menggambarkan betapa sulitnya menjadikan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas.
Jika di Jakarta saja pemakai angkutan umum belum mencapai seperlima perjalanan harian, maka di kota-kota lain yang infrastrukturnya jauh lebih terbatas, kondisinya hampir pasti lebih rendah lagi. Dengan realitas seperti ini, wajar bila Harhubnas tahun ini menjadi momen refleksi: apakah sistem transportasi kita benar-benar sudah menjadi wujud pengabdian kepada masyarakat luas?
Kondisi itu semakin jelas ketika menengok ke kota-kota di luar Jakarta. Angkutan umum perkotaan di banyak daerah kini menghadapi kemunduran. Bus kota nyaris hilang, angkot tersisa dalam jumlah sedikit dengan armada tua, sementara layanan BRT berjalan setengah hati.
Akibatnya, masyarakat makin bergantung pada sepeda motor atau ojek daring untuk mobilitas harian. Fenomena stagnasi ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan buah dari lemahnya tata kelola transportasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Potret Suram Angkutan Umum Kita
Situasi ini terlihat nyata di sejumlah kota besar. Di Bandung, jumlah angkot terus menyusut dan sebagian besar armadanya sudah tua serta tidak layak jalan. Di Semarang, layanan BRT yang beroperasi sejak 2009 belum mampu menarik minat besar, jumlah penumpangnya masih relatif kecil dibanding kebutuhan mobilitas harian.
Di Palembang, LRT yang dibangun untuk Asian Games 2018 hanya mengangkut belasan ribu penumpang per hari, jauh dari kapasitas yang tersedia. Sementara di Makassar, operasional BRT Trans Mamminasata tidak stabil.
Sebagian koridor sempat terhenti karena subsidi pusat dihentikan, dan kini hanya bertahan terbatas berkat dukungan subsidi dari program Bus Trans Sulsel yang dijalankan pemerintah provinsi.
Jika kota besar menghadapi masalah serius, maka di kota-kota kecil dan menengah kondisinya bahkan lebih memprihatinkan. Denpasar, yang dikenal sebagai kota wisata dunia, pada 2007 hanya mencatat tingkat penggunaan angkutan umum sekitar 3–4 persen.
Studi yang lebih baru pada 2016 pun masih menunjukkan angka rendah, sekitar 8,8 persen, menandakan tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Warga maupun wisatawan nyaris tidak memiliki pilihan selain motor atau mobil.
Di banyak kota menengah lain, angkot hampir punah, jadwal tidak menentu, dan armada yang tersisa rata-rata sudah berusia tua. Ironi besar: kota-kota yang seharusnya menampilkan wajah Indonesia kepada dunia justru memperlihatkan wajah transportasi publik yang nyaris tidak ada.
Angkutan Umum Terpuruk: Cermin Tata Kelola yang Lemah
Persoalan angkutan umum di Indonesia tidak hanya berhenti pada soal armada tua atau layanan yang merosot, melainkan berakar pada kebijakan dan tata kelola transportasi yang lemah. Pembangunan transportasi publik masih sangat berpusat di Jakarta.
Proyek-proyek megah seperti MRT, LRT, hingga Kereta Cepat menelan triliunan rupiah, namun manfaatnya terutama dirasakan masyarakat di Jabodetabek. Sementara itu, kota-kota lain hanya menjadi penonton, padahal kebutuhan mobilitas mereka tidak kalah mendesak.
Jakarta tentu berhak mendapatkan layanan modern, tetapi negara juga berkewajiban memastikan kota-kota di luar ibu kota tidak dibiarkan bertahan dengan angkutan umum seadanya.
Sejak otonomi daerah berlaku, urusan transportasi perkotaan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, banyak daerah tidak mampu secara fiskal atau justru tidak menaruh perhatian. Anggaran lebih banyak diarahkan ke proyek fisik yang mudah terlihat, sementara subsidi bagi angkutan umum kerap diabaikan.
Ego sektoral, birokrasi berbelit, hingga praktik pungutan liar memperburuk keadaan. Di sisi lain, peran Kementerian Perhubungan pun sering tidak ditindaklanjuti dengan konsisten: regulasi dibuat, program diluncurkan, tetapi keberhasilannya sepenuhnya bergantung pada komitmen daerah.
Karena itu, kementerian tidak bisa hanya bersikap pasif. Ia perlu hadir secara aktif mendampingi daerah, baik secara teknis, operasional, maupun administratif, agar program, seperti Buy the Service (BTS) benar-benar berjalan lancar dan berkelanjutan.
Subsidi Terhenti, Mobilitas Warga Tersendat
Tak hanya soal kewenangan daerah, transportasi umum juga rapuh karena skema subsidi yang tidak berkelanjutan. Transportasi publik pada dasarnya sangat sulit bertahan tanpa dukungan dana pemerintah. Skema Buy the Service (BTS) sempat dijalankan pemerintah pusat, tetapi kerap terhenti begitu anggaran habis.
Pemerintah daerah pun enggan melanjutkan dengan APBD, sehingga layanan terputus di tengah jalan. Akibatnya, BRT yang semula digadang-gadang sebagai solusi justru berhenti beroperasi, bus mangkrak, dan penumpang kehilangan kepercayaan. Tanpa pendanaan berkesinambungan, setiap program hanya berumur pendek dan gagal memberi dampak nyata.
Kerapuhan itu semakin terlihat pada moda angkot, yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas warga di banyak kota. Moda ini dibiarkan berjalan tanpa arah dan tanpa perlindungan. Tidak ada upaya serius untuk merestrukturisasi trayek, memperbarui armada, atau membenahi pola bisnis.
Operator kecil harus bertahan sendiri, sementara jumlah penumpang terus menurun. Padahal, dengan manajemen yang tepat, angkot bisa berfungsi lebih baik: di kota besar sebagai penghubung BRT, dan di kota lain tetap menjadi angkutan utama masyarakat. Membiarkan angkot merosot sama saja memutus akses mobilitas bagi warga miskin yang masih sangat bergantung pada moda ini.
Gengsi dan Tata Kota Buruk: Kombinasi Mematikan Angkutan Umum
Citra buruk angkutan umum juga memperparah keadaan. Bagi banyak orang, bus atau angkot identik dengan lambat, kotor, penuh sesak, dan tidak aman. Stigma ini terbentuk dari pengalaman panjang bertahun-tahun.
Bagi sebagian kalangan, naik angkot bahkan dianggap menurunkan gengsi, sehingga kendaraan pribadi dipandang lebih layak untuk menjaga status sosial. Akibatnya, kepercayaan terhadap angkutan umum terus merosot, meski sebenarnya moda ini bisa jauh lebih efisien dan ramah lingkungan jika dikelola dengan baik.
Semua persoalan itu semakin diperparah oleh tata ruang kota yang buruk. Banyak kota berkembang secara menyebar tanpa perencanaan yang ketat, dengan perumahan, kawasan industri, dan pusat belanja baru berdiri jauh di pinggiran.
Pola pembangunan yang berorientasi pada kendaraan pribadi semakin dominan: jalan raya dan flyover terus diperlebar, sementara fasilitas parkir kendaraan diperluas, sedangkan akses angkutan umum jarang diprioritaskan.
Lebih parah lagi, izin pembangunan kawasan baru kerap diberikan tanpa mempertimbangkan kewajiban menyediakan layanan angkutan umum, membuat motor dan mobil pribadi menjadi satu-satunya pilihan. Semua itu menjadikan angkutan umum makin kehilangan daya saing, dan kota semakin terjebak dalam kemacetan dan polusi.
Semua faktor di atas menciptakan lingkaran masalah yang tak berujung: layanan angkutan umum yang buruk membuat penumpang enggan kembali naik angkutan umum, pendapatan operator turun, armada tidak mampu dipelihara dengan baik, lalu kualitas layanan makin merosot.
Kondisi itu mendorong semakin banyak orang meninggalkan angkutan umum, sehingga jumlah penumpang terus berkurang. Siklus ini berputar semakin cepat hingga angkutan umum benar-benar mengalami mati suri.
Bakti Transportasi, Momentum Menghidupkan Kembali Angkutan Umum
Mati surinya angkutan umum mencerminkan lemahnya tata kelola di berbagai tingkat pemerintahan. Di pusat, Kementerian Perhubungan sering tidak optimal karena kebijakannya kurang sesuai dengan kebutuhan daerah dan lambat menyesuaikan diri dengan dinamika baru.
Di daerah, pemerintah kota dan kabupaten juga tidak lebih baik: kemauan politik rendah, kompetensi terbatas, dan anggaran minim. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan pada angkutan umum dan beralih ke kendaraan pribadi.
Karena itu, solusi yang fundamental perlu diarahkan pada langkah mendasar namun tidak mudah: mengalihkan sebagian anggaran pembangunan jalan dan flyover untuk subsidi serta revitalisasi angkutan umum, sekaligus memaksa integrasi kebijakan tata ruang dengan transportasi. Tanpa keberanian seperti ini, lingkaran masalah yang melemahkan angkutan umum tidak akan pernah terputus.
Dan di sinilah pentingnya menjadikan Harhubnas lebih dari sekadar acara seremonial, melainkan momentum untuk menata ulang arah kebijakan transportasi kita. Tema Harhubnas 2025 “ Bakti Transportasi untuk Negeri ” seharusnya menjadi pengingat. Bakti itu tidak boleh berhenti pada proyek-proyek megah di ibu kota atau peringatan tahunan belaka.
Bakti transportasi yang sejati adalah ketika seorang guru di Medan, seorang nelayan di Makassar, dan seorang pekerja pabrik di Bandung bisa pulang-pergi dengan angkutan umum yang layak, terjangkau, dan bermartabat—karena di situlah wajah negara hadir dalam kehidupan warganya yang paling sederhana.
Ditulis Oleh: Muhamad Akbar, Pemerhati Transportasi
Disclaimer: Segala bentuk risiko yang timbul dari tulisan ini adalah tanggungjawab penulis.